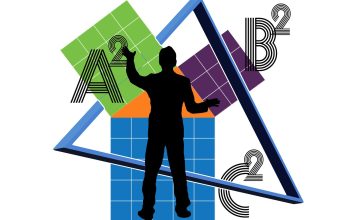Fenomena penggunaan kecerdasan buatan (AI) di kalangan pelajar global kini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan sekaligus tak terelakkan. Sebuah riset terbaru menyingkap fakta bahwa remaja di seluruh dunia tidak lagi hanya menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi juga menjadikannya tempat mencari kenyamanan emosional dan nasihat hidup. Sementara para siswa semakin intim dengan teknologi ini, institusi pendidikan dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi tampak kewalahan menyesuaikan diri dengan realitas baru ini.
Ilusi Keakraban Semu
Studi yang melibatkan 545 siswa sekolah menengah di Kashmir memberikan gambaran mendesak yang mencerminkan pola serupa di Kamboja, Hungaria, dan Eropa secara luas. Hampir 96% siswa menggunakan ChatGPT secara rutin untuk keperluan sekolah. Namun, angka statistik hanyalah puncak gunung es. Para siswa ini mendeskripsikan alat AI bukan sekadar asisten akademik, melainkan sebagai pendamping dalam pengambilan keputusan.
“ChatGPT terasa seperti teman yang bisa dipercaya,” ujar seorang remaja. Siswa lain bahkan mengaku menggunakan AI layaknya sahabat tempat berbagi perasaan ketika tidak ada orang lain yang bisa diajak bicara. Ketergantungan emosional ini sangat meresahkan. Model bahasa besar ini tidak dirancang untuk tujuan terapeutik, dan insiden global baru-baru ini telah menyoroti bahaya ketika remaja memperlakukan chatbot sebagai terapis. Namun, daya tariknya sulit ditolak: AI nyaman, sabar, tidak menghakimi, dan selalu tersedia 24 jam. Bagi generasi yang tumbuh dengan gratifikasi digital instan, tawaran ini terlalu menggiurkan.
Kesenjangan Pengetahuan dan Kemalasan Kognitif
Ironisnya, tidak ada yang mengajarkan mereka cara menggunakan teknologi ini dengan benar. Siswa belajar secara otodidak melalui media sosial dan YouTube, bukan lewat instruksi terstruktur di kelas. Hal ini menciptakan ketimpangan yang nyata; mereka yang memiliki akses internet lebih baik dan kemampuan bahasa yang mumpuni akan unggul, sementara yang lain tertinggal. Tanpa pelatihan formal, siswa kehilangan pemahaman kritis tentang cara kerja sistem AI dan mengapa sistem tersebut bisa memproduksi informasi palsu. Mereka mahir memberi perintah (prompting), namun gagap dalam mengevaluasi jawaban.
Di sisi lain, para siswa sebenarnya merasakan ambivalensi mendalam. Ada perasaan bersalah yang menjalar, seperti pengakuan seorang siswa berusia 16 tahun yang merasa menggunakan ChatGPT untuk tugas sekolah terasa seperti mencontek. Siswa lain mengakui bahwa ia merasa kemampuan kognitifnya tidak terpakai, bahkan menjadi terlalu malas untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disajikan AI. Mereka sadar ada batasan etika yang kabur dan kemalasan berpikir yang mulai menggerogoti, namun mereka terus melakukannya karena semua orang melakukannya, dan karena belum ada otoritas dewasa yang secara tegas melarang atau mengarahkannya.
Kekosongan Regulasi di Sekolah
Masalah utamanya terletak pada respon lambat institusi pendidikan. ChatGPT diluncurkan pada November 2022, dan pada saat sekolah mulai mendiskusikan kebijakan, siswa sudah mengintegrasikannya ke dalam rutinitas harian. Studi tersebut mengungkapkan kegagalan institusional yang cukup parah: 77% siswa melaporkan sekolah mereka tidak memiliki sikap resmi terkait alat AI.
Kekosongan kebijakan ini membuat semua pihak tidak siap. Guru kesulitan menilai tugas karena sering kali menjumpai pekerjaan rumah yang “terlalu sempurna” namun hampir mustahil membuktikan bahwa itu buatan AI. Akibatnya, penilaian menjadi tantangan besar. Ketika siswa diminta menjelaskan penalaran mereka secara langsung, banyak yang tidak mampu menjawab. Seorang guru memperingatkan bahwa dengan penggunaan AI yang merajalela, siswa tidak berkembang secara intelektual; mereka hanya menyelesaikan tugas, bukan membangun kemampuan kognitif.
Adaptasi Strategis di Perguruan Tinggi
Sementara sekolah menengah masih berkutat dengan masalah etika dasar dan ketergantungan siswa, sektor pendidikan tinggi mulai mengambil langkah yang lebih strategis untuk “menulis ulang” sistem operasi mereka. Universitas kini dihadapkan pada tantangan bukan lagi soal apakah harus beradaptasi, melainkan seberapa cepat mereka bisa melakukannya.
Prof. Dr. Zoltán Rajnai, Wakil Rektor Urusan Umum di Universitas Óbuda, Hungaria, memberikan perspektif berbeda dalam episode Transform Talks. Ia menggambarkan bagaimana AI mengubah makna mengajar, belajar, dan mengelola universitas modern. Universitas Óbuda, melalui kemitraan satu dekade dengan Huawei, telah menjadi pionir di Hungaria dengan menerapkan Wi-Fi 7 di seluruh kampus sebagai bagian dari strategi menyambut masa depan berbasis AI.
Bagi institusi pendidikan tinggi yang progresif, AI bukan lagi musuh, melainkan sekutu. Teknologi ini mendukung administrasi, meningkatkan riset, memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, serta meningkatkan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini membebaskan para pendidik untuk fokus pada pekerjaan akademik yang bernilai lebih tinggi, alih-alih terjebak dalam tugas administratif.
Membangun Literasi Digital yang Sehat
Melihat kesenjangan penanganan antara sekolah menengah dan perguruan tinggi, jelas bahwa solusi “pelarangan total” bukanlah jawaban. Sekolah harus segera menyusun kebijakan tertulis yang jelas—bukan larangan membabi buta, tetapi pedoman bijak yang mendefinisikan penggunaan yang tepat.
Diperlukan program literasi AI terstruktur yang mencakup keterampilan teknis dan pertimbangan etis. Program ini harus mengajarkan cara mengevaluasi alat, mendeteksi bias, dan yang terpenting, mempertahankan keterampilan berpikir kritis. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa guru yang optimis, penggunaan AI di sekolah bisa berdampak positif jika dikelola dengan benar. Jika digunakan secara bijak, AI dapat mempersonalisasi pembelajaran dan membantu siswa yang kesulitan. Namun jika digunakan sembarangan, ia hanya akan menjadi tongkat penyangga yang melemahkan otot-otot intelektual yang seharusnya ia perkuat. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan generasi muda siap menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh AI.